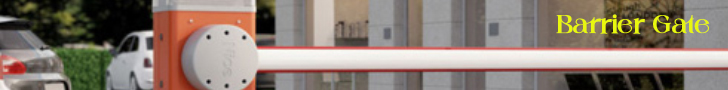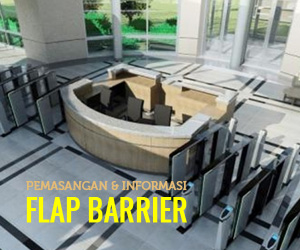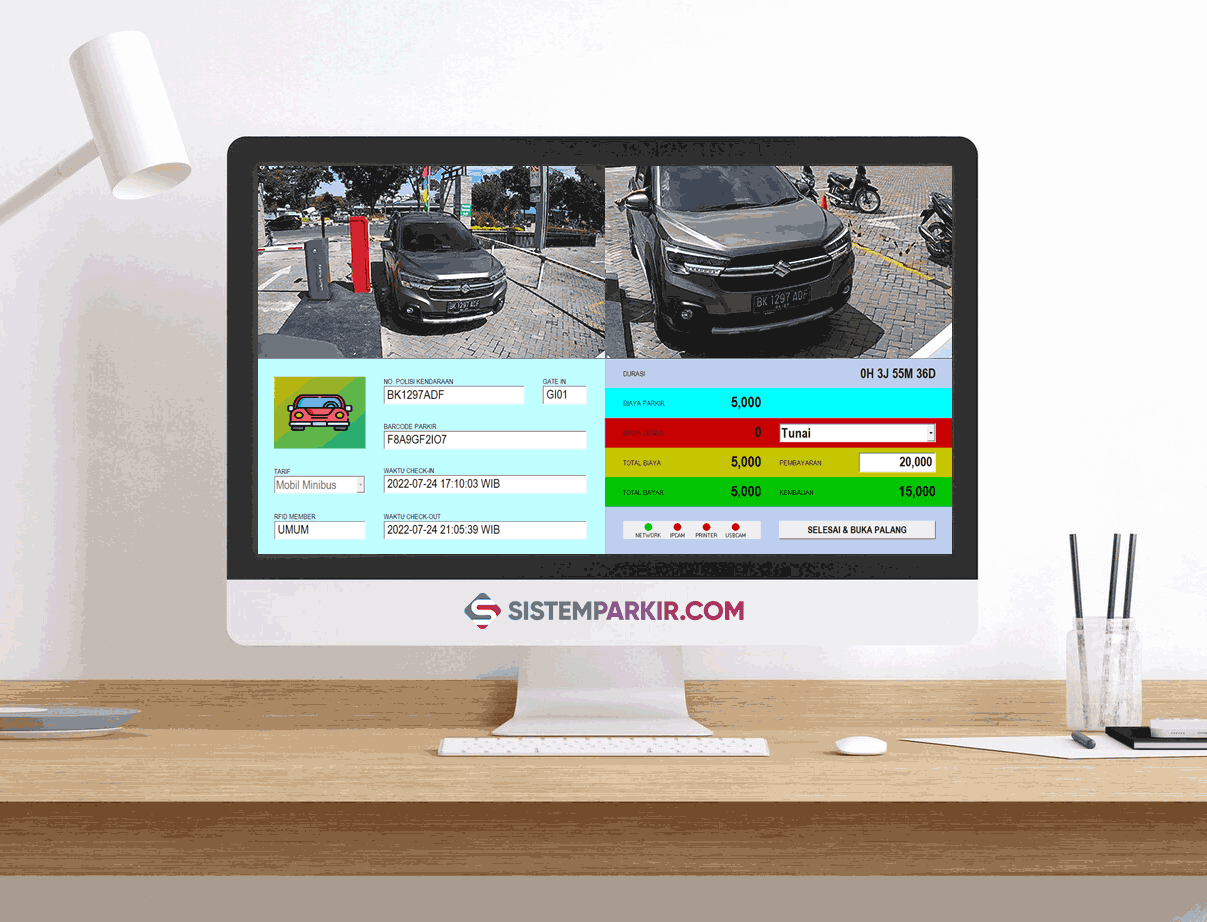KERAJAAN Aru (Haru) dalam berbagai literatur disebut sebagai sebuah kerajaan besar pada sekitar abad ke-13 hingga ke-16. Ini kemudian terekam dalam berbagai jurnal perjalanan cendekiawan luar, seperti Tome Pires dan Mendes Pinto. Yang menarik, dalam perjalanannya, sepertinya ada data emosional yang membuat simpulan bahwa Kerajaan Aru adalah Karo saat ini.
Benarkah? Tak ada yang tahu pasti. Walau begitu, dari data perjalanan, terutama jika menyingkirkan data emosional, kita bisa mencari petunjuk. Maksud data emosional di sini adalah kemauan untuk menceritakan sesuatu yang nyaris seluruhnya hanya mengandalkan subjektivitas, sehingga objektivitasnya diragukan. Subjektivitas itu, misalnya, muncul dari penamaan yang cenderung sebatas cocoklogi.
Masuk akal sih menganalogikan Aru atau Haru menjadi Karo. Ada kesamaan bunyi. Karena itu, ketika pada tahun 1365 M Prapanca menyebut satu nama tempat yakni Harw dalam canto ke-13 bait pertama baris ke-4 dalam kakawin Desawar?nana, para ahli seperti bersepakat bahwa maksudnya adalah Aru. Masih ada bunyi yang cenderung mempunyai bunyi yang relatif ada kesamaan dan ditafsir juga sebagai Aru.
Bunyi itu adalah Teradaru dan Isola Daru.Teradaru secara harfiah berarti Aru Darat, sedangkan Isola Daru secara harfiah berarti Aru Pulau. Namanya bahasa. Ia punya bunyi. Kadang bisa dikait-kaitkan meski tak terkait. Maka, Sungai Barumun dikaitkan dengan Aru karena ada bunyi "Aru" pada Barumun. Bisa saja terkait. Bahkan, bisa terlihat sangat logis dari data geografis.
Tetapi, sebagai bahasa, tak semua yang bunyi relatif sama dapat disamakan meski, ya, bisa dikaitkan dengan ilmu cocoklogi. Maaf, kata "bujang" di Batak relatif kasar dan kotor. Kadang, jatuh-jatuhnya arti bahasa ini tak lagi pada jenis organ tubuh, melainkan pada makian. Namun, dalam bahasa Nasional, kata ini tidak berarti kasar. Kata ini mengacu pada sudah dewasa, tapi belum menikah.
BACA JUGA: Kompetensi Emosional dengan Pembelajaran Diferensiasi
Bukan berarti bahwa bujang adalah tak laku. Justru, terkadang ini menjadi pilihan hidup sehingga muncullah kata membujang yang artinya pilihan sadar untuk tak menikah. Biarawati dan biarawan bisa dimasukkan dalam kategori ini. Artinya, kedua bahasa yang sama ini ternyata meski sama, tetapi tak benar-benar sama. Namun, justru di sinilah hebatnya ilmu cocoklogi. Semua bisa dicocokkan.
Kita, misalnya, bisa menariknya jauh. Bahwa kata bujang pada bahasa Batak mengacu pada organ kelamin sehingga dapat diasosiasikan sebagai kawin tak kawin. Cocok? Ya, cocok saja. Tak cocok? Bisa juga. Itulah permainan bahasa. Kata yang sama tak mempunyai rasa yang sama. Bagi salah satu subetbis Batak, kata bujing bisa buruk. Sebab, sebagai orang Toba, saya mengartikannya berbeda.
Ternyata, di Mandailing, bujing-bujing artinya justru sangat bagus. Sama dengan kata "kau". Di Karo, "kau" rasanya sangat kasar. Di bahasa Toba, ada lagi bahasa yang tak tuntas rasanya. Orang tua selalu mengatakan kepada kami bahwa jika memanggil orang tua, kita harus menyebutnya "hamu" (kamu), bukan "ho" (kau). "Ho" tidak sopan untuk orang yang lebih tua. Tetapi, faktanya, kata "ho" justru dipakai untuk Tuhan. Rasa bahasanya tak tuntas bukan?
Maksud saya, mengartikan Aru menjadi Karo ada benarnya, ada juga tak benarnya. Tergantung ilmu apa yang kita pakai. Tergantung, data apa yang kita gunakan. Tergantung, apa tujuan kita. Namun, dari data literatur sejauh ini, saya melihat bahwa Aru dan Karo adalah dua hal yang berbeda. Aru cenderung kepada Melayu Deli sementara Karo cenderung ke Batak dan bukannya Deli.
Kita bisa berdebat panjang soal kata "Melayu". Sebab, ada orang yang menafsirkan bahwa "Melayu" tak sebatas nama etnis, tetapi juga pencapaian. Sudah Melayu berarti sudah maju dan sudah beragama. Sudah Islam. Sebaliknya, Batak juga tak selalu tentang etnis. Konon, mereka yang masih terbelakang disebut sebagai Batak sehingga tampak bahwa Batak lebih pada kondisi ketertinggalan daripada sebagai etnis.
Begitulah Aru. Ia menjadi misterius sehingga kadang diceritakan secara emosional. Ilmu-ilmu kita ternyata belum cukup untuk mendefinisikannya secara tuntas. Memang, dari berbagai data literatur, Aru cenderung bukan berarti Karo saat ini. Tetapi, kadang, data-data yang kita dapat juga sangat ekstrem dan konon malah sangat berjauhan atau berseberangan.
Sir Richard Winstedt menggunakan Aru dan Deli (nama satu kerajaan pasca tahun 1600an, termasuk di dalam wilayahnya adalah kawasan situs Kota Cina) secara bergantian untuk menyebut nama satu tempat dalam karyanya A History of Malaya; sementara Encyclopoedia van Nederlandsch-Indie mengusulkan Teluk Aru yang terletak sekitar 70 km arah utara dari Kota Cina sebagai tempat kedudukan Aru.
Ternyata, ada data yang ekstrem. GR Tibbets termasuk di dalamnya adalah sebab meletakkan Aru di muara Sungai Panai, yang terletak sekitar 200 km arah selatan dari Kota Cina (Milner 1978 dalam Soedewo 2020, 90). Dalam hal ini, Aru bisa menjadi Batak. Alasannya dilihat dari fungsi sungai dalam kehidupan kita. Tetapi, bisa juga menjadi tidak. Tergantung tujuan kita: mencari data emosional atau mencari objektivitas.
====
Penulis Guru SMAN 1 Doloksanggul, Penyuka Sastra dan Budaya.
====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG), data diri singkat (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]