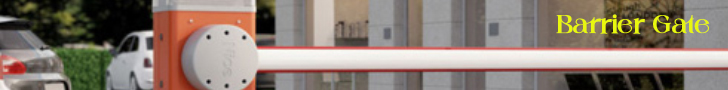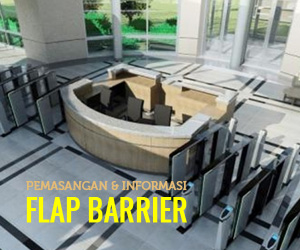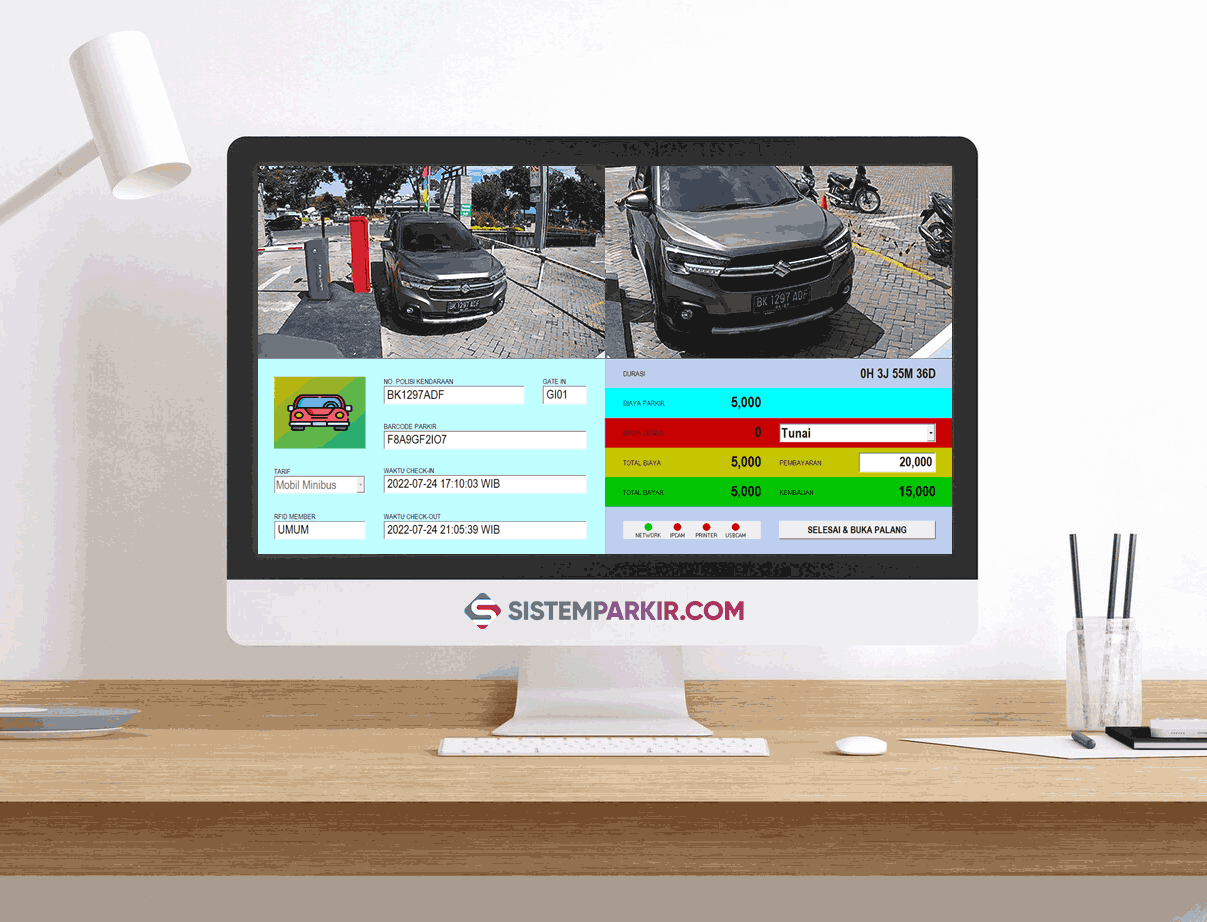SUATU ketika, R Murray Thomas melakukan penelitian pendidikan dari perspektif sosio-antropologis, yaitu The Prestige of Teachers in Indonesia” (1962). Kesimpulannya: guru Indonesia pada saat itu merupakan role model, panutan, istimewa, serta memiliki pengaruh besar di masyarakat. Saat itu, berbagai literatur juga menyebutkan bahwa guru selalu dimintai pendapat dan nasihatnya oleh masyarakat. Menariknya, latar historis pada saat itu justru menempatkan bahwa guru belum sejahtera. Penelitian Thomas ini lantas diuji kembali oleh Misbach (2013).
Dalam penelitian itu, Misbach ingin melihat apakah guru masih saja jadi panutan bagi siswa sepanjang dekade tahun 2000-2013 atau tidak. Ternyata, mulai ada pergeseran. Sebab, sejak Ujian Nasional (UN) menjadi penentu kelulusan, 2004-2013, terjadi peningkatan jumlah oknum guru melakukan contek massal: lebih dari 1.300 kasus. Hipotesis saya pun menguat: bahwa otonomi daerah telah memaksa guru untuk ramai-ramai menukangi keberhasilan siswa per daerah. Dalam hal ini, otonomi daerah telah berkontribusi untuk membuat guru wajib membeo pada penguasa setempat.
Taruhannya tentu sangat fatal: integritas diobral. Pasalnya, jika guru tidak “patuh”, ia bisa dimutasi ke tempat terjauh atas nama "ASN bersedia ditempatkan di mana pun". Jika hal ini nyata adanya, jelas sekali bahwa pendidikan kita telah beraroma feodal lantaran guru akan selalu takut pada ancaman mutasi. Apalagi kemudian, dalam banyak peristiwa, mutasi tak lagi sebatas gertak sambal. Setidaknya, Bank Dunia dalam studinya pernah menyebutkan bahwa setiap pilkada, ada penambahan penerimaan guru dengan besaran 800 per wilayah. Setiap pilkada pula, probabilitas guru untuk disertifikasi meningkat tiga persen.
Contoh Kontemporer
Jika saja diperbolehkan mengambil contoh kontemporer terkait isu di atas, kini, di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, setelah pilkada usai, sedang hangat-hanganya dibicarakan soal mutasi guru oleh bupati terpilih ke tempat terjauh (75 km). Banyak warga menyakini bahwa mutasi guru-wanita yang hampir pensiun ini adalah efek langsung dari pilkada setempat. Apa pasal, misalnya, sehingga harus memutasi guru yang hampir pensiun ke tempat terjauh, sementara sekolah yang bersangkutan sedang tidak kelebihan guru, misalnya? Karena itu, dugaan mutasi karena efek pilkada bukan isapan jempol.
Tetapi, mari tinggalkan kasus itu. Sekarang, mari berefleksi. Bayangkanlah, jika fenomena mutasi guru ini selalu berulang, maka kemungkinan guru semakin tidak merdeka akan semakin besar juga, bukan? Padahal, kehadiran guru adalah untuk memerdekakan siswa. Lantas, bagaimana mungkin ia bisa memerdekakan siswanya jika ia saja masih terbelenggu? Dalam pada inilah tulisan ini dibuat agar kita melindungi guru dari gerakan beraroma feodal politik-penguasa. Guru harus tetap merdeka dari tarik-menarik politik. Jika guru selalu ditakuti mutasi hanya karena politik, dikhawatirkan akan terjadi penurunan kualitas pembelajaran di sekolah.
Tentu saja saya tidak sedang khawatir berlebihan. Ada banyak studi terkait itu. Menurut Rhenald Kasali, misalnya, bahwa salah satu yang menjadi momok bagi ASN (menurut saya: terutama guru) adalah kehadiran pemimpin baru. Padahal, dalam demokrasi, pemimpin baru adalah keniscayaan. Namun, keniscayaan dengan lahirnya pemimpin baru yang mestinya membuat suasana dan harapan baru justru berbuntut pada tekanan baru: ancaman mutasi. Ancaman seperti ini tentu saja sangat tidak baik. Kata Maxwell (2000), misalnya, bahwa aparatur yang demikian akan membelenggu masa depan suatu bangsa.
BACA JUGA: Sebab Bagi Milenial Rumah Juga Tempat Kerja
Soalnya, hal itu akan melahirkan kepemimpinan level terendah: yang diakui keberadaannya karena ia pemegang SK dan bawahan tunduk hanya karena keharusan struktural. Dampak yang lebih fatal lagi adalah ketika loyalitas pada pemberi jabatan menjadi lebih penting ketimbang terhadap publik. Perhatian terhadap kinerja, apalagi pengembangan sumber daya manusia, juga bukan dianggap sebagai hal yang penting lagi. Sampai di titik ini kiranya sudah terang bagi kita bahwa ancaman, terutama bagi guru, akan semakin mengacaukan proses pembangunan manusia kita.
Agar Kita Sadar
Sudah banyak bukti terkait itu. Berkali-kali, misalnya, kita direpotkan distribusi guru yang tidak merata, juga oleh meledaknya keran guru honorer sebagai balas jasa politik-penguasa. Semua hal itu terjadi adalah karena politik-penguasa yang bersalin rupa menjadi raja-raja kecil di daerah. Dan, tanpa kita sadari, hal inilah yang pada akirnya bermuara pada, mengutip hasil analisis Wartawan Kompas Ester Lince Napitupulu dalam satu tajuknya "Guru Belum Merdeka" (Kompas, 2 Mei 2014): penurunan kualitas guru. Pasalnya, otonomi daerah yang menciptakan raja-raja kecil membuat guru harus takluk dan membeo pada kekuasaan.
Akibatnya, guru tak bisa lepas dari dinamika politik di tingkat kabupaten atau kota. Guru tak punya pilihan lain, kecuali membeo. Praktis, tak ada kemerdekaan dalam dirinya. Padahal, sejatinya, guru adalah kekuatan dan kemerdekaan itu sendiri. Dari tangan merekalah nantinya akan lahir pemikir masa depan, bahkan pembebas. Karena itu, mereka seharusnya menjadi pundak yang kuat bagi cita-cita bangsa ini, terutama dalam menyongsong satu abad negara ini. Namun, mengutip sebagian artikel Rhenald Khasali, posisi guru berstatus ASN justru sangat paradoks: kuat dan penting, sekaligus lemah (Kompas, 14/03/2015).
Begitu penting dan kuatnya, misalnya, sehingga dalam menjalankan tugasnya mereka disumpah, diseleksi dari puluhan ribu orang untuk menegakkan aturan, memegang mandat UU. Namun, di sisi lain, desain organisasi, aturan, dan perilakunya membuat mereka lemah: strukturnya mekanistik, jenjang karier dikaitkan dengan lama tugas, gaji tetapnya rendah, dan terutama ada pula ancaman untuk dimutasi. Guru yang sudah tinggal bersama keluarga tentu saja akan sulit untuk berpisah dengan keluarga. Karena itu, jalan terbaik baginya agar tak dimutasi adalah mempertaruhkan profesionalisme: membeo pada kekuasaan.
Baiklah, mari langsung ke poin tulisan ini. Sejujurnya, sebagai guru, sama sekali tak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin agar kita sadar bahwa sebagai pundak pemikul cita-cita bangsa, sudah sebaiknya pengelolaan guru diresentralisasi kembali untuk menjaga guru dari rongrongan politik-daerah. Teknisnya, misalnya, biarkan satu dirjen khusus untuk mengatur guru. Jika tidak, di samping menjadi alat politik yang rentan digertak mutasi atas nama "siap ditempatkan di mana pun", guru kita akan semakin jauh dari kemerdekaan. Padahal, kita sama-sama tahu bahwa hanya guru yang merdeka yang bisa membuat siswa meredeka. Semoga!
====
Penulis Guru Bahasa Indonesia SMAN 1 Doloksanggul, Humbang Hasundutan, Aktif Berkebudayan dan Berkesenian di PLOt (Pusat Latihan Opera Batak) dan TWF (Toba Writers Forum)
====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel/surat pembaca) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG), data diri singkat/profesi/kegiatan (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter (surat pembaca maksimal 2.000 karakter). Gunakan kalimat-kalimat yang singkat (3-5 kalimat setiap paragraf). Judul artikel/surat pembaca dibuat menjadi subjek email. Tulisan TIDAK DIKIRIM DALAM BENTUK LAMPIRAN EMAIL, namun langsung dimuat di BADAN EMAIL. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel/surat pembaca sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan/surat pembaca Anda ke: [email protected]