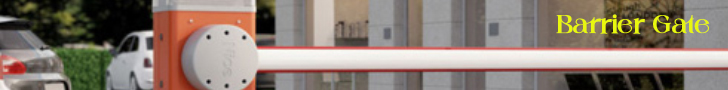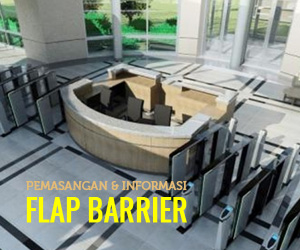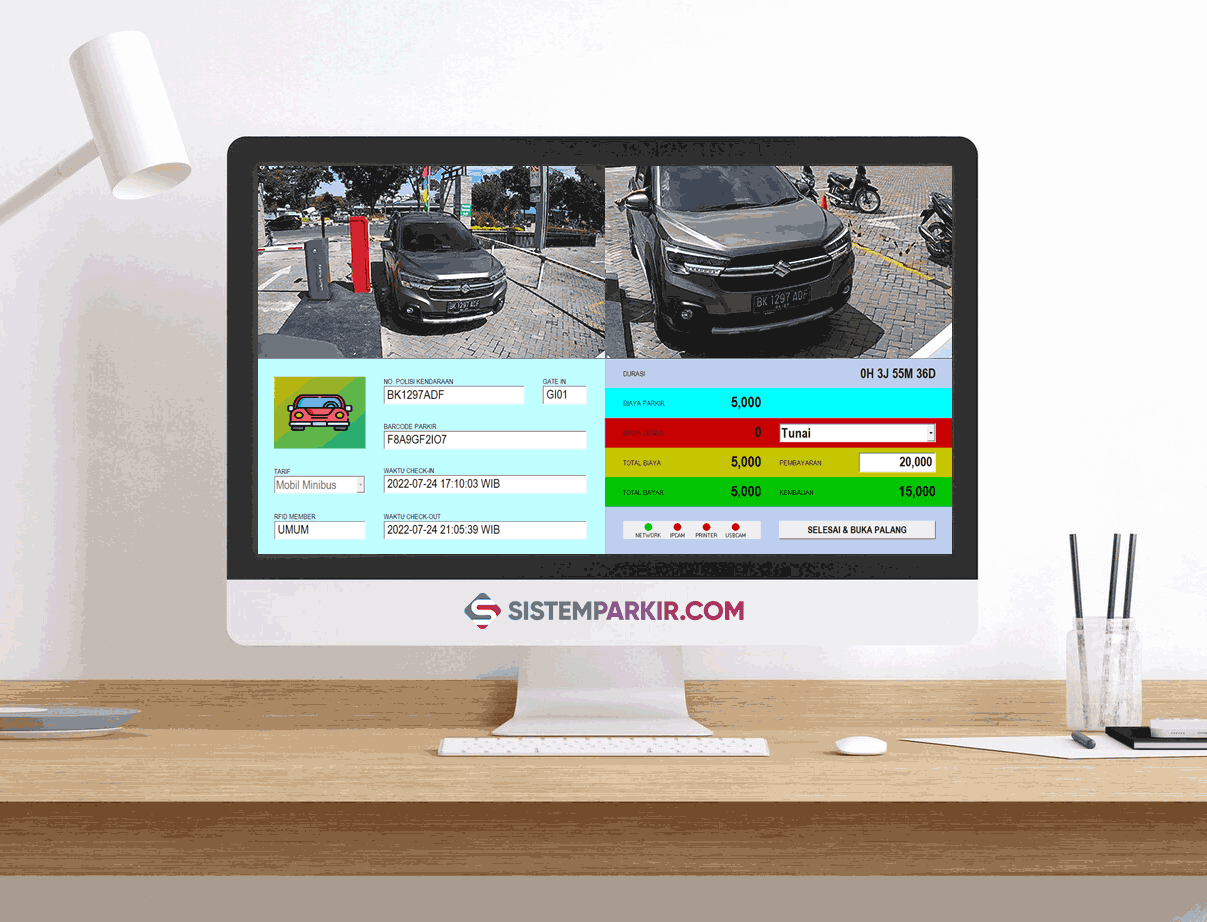"There are worse crimes than burning books. One of them is not reading them". (Ada kejahatan-kejahatan yang lebih buruk daripada membakar buku. Salah satunya adalah tidak membacanya).
Ungkapan yang dinyatakan oleh Ray Douglas Bradbury, sastrawan berkebangsaan Amerika itu ada benarnya dan sangat relevan dengan masa sekarang. Malah, menurut saya, ada kejahatan lain yang lebih keji, yaitu membajak buku. Pasalnya, pembajakan buku tidak cuma merampas hak cipta dan kekayaan intelektualitas sang penulis. Jika ditarik lebih jauh, membajak buku dapat pula berarti mengkebiri hak-hak yang menjadi hajat hidup banyak orang. Atau singkatnya, membajak buku merupakan pekerjaan maling. Ya, maling intelektualitas!
Sebelum beredar di pasaran, sebuah buku harus terlebih dahulu menjalani serangkaian proses panjang. Proses itu melibatkan sejumlah pihak. Rinciannya begini, setelah penulis menyelesaikan naskah, ia akan berhubungan dengan penerbit. Di penerbit, naskah itu harus di-review terlebih dahulu. Jika layak, maka akan berlanjut ke proses editing (penyuntingan), layout (tata letak), desain cover dan proses cetak. Dalam setiap tahapan itu tentu sebuah penerbit membutuhkan biaya yang tidak sedikit guna membayar gaji para pekerja.
Para pebisnis buku bajakan tidak perlu melalui proses panjang itu. Mereka tidak diwajibkan membayar royalti kepada penulis. Mereka tidak membayar upah pekerja untuk tugas-tugas yang sudah diuraikan di atas. Inilah yang menjadi alasan mengapa harga sebuah buku bajakan bisa jauh lebih murah bila dibandingkan dengan versi aslinya. Alhasil buku bajakan berkembang pesat menjadi sebuah industri yang sangat menggiurkan. Hampir di setiap kota-kota besar di Indonesia, kita bisa menemukan kios-kios buku murah yang sebagian besar buku-bukunya diperoleh dengan cara mencetak ulang secara ilegal. Sekarang, industri gelap ini mulai merambah ke ranah digital dan konsumennya pun kian hari kian membludak.
Dilema
Tanpa bermaksud membela, pilihan untuk membeli buku-buku bajakan—meski jelas-jelas merupakan perbuatan yang salah di mata hukum—bisa jadi diambil karena situasi-situasi sulit yang memaksa. Situasi pertama adalah masalah harga. Buku-buku original apalagi dengan label best seller, harganya bisa membumbung tinggi. Dengan daya beli orang Indonesia yang belum terlalu mendukung untuk menjadikan buku sebagai barang kebutuhan, buku-buku bajakan menjadi pilihan paling rasional bagi sebagian besar masyarakat kita. Situasi kedua, buku-buku referensi keilmuan tahun-tahun lawas namun masih cukup relevan untuk keperluan akademis di kalangan dosen dan mahasiswa jarang ditemukan di toko-toko buku besar. Sebaliknya, di kios-kios buku bekas dan toko-toko buku online, buku-buku seperti itu cenderung mudah untuk ditemukan. Dan, sekali lagi, dengan harga yang miring.
Fenomena-fenomena itu dimanfaatkan dengan sangat jeli oleh para pelaku pembajakan buku. Dengan modal sedikit, mereka mencetak ulang buku-buku original dengan sebutan kw, non-ori atau repro untuk memperhalus narasi bajakan yang konotasinya negatif dan buruk bagi strategi pemasaran (marketing strategy). Apalagi di era internet sekarang, buku-buku versi cetakan PDF bisa dengan mudah diunduh. Maka, bisnis buku bajakan pun kian tumbuh subur saban hari.
Ini menjadi PR bagi pemerintah. Di tengah persoalan indeks literasi bangsa ini yang belum beranjak dari keterpurukan dan masih rendahnya jumlah buku-buku bermutu yang dihasilkan, maraknya industri buku bajakan merupakan pukulan telak terhadap penulis dan penerbit. Jika dibiarkan terus-menerus bukan tidak mungkin para penulis akan urung menelurkan karya-karya baru. Mereka juga manusia yang harus tetap mengepul asap di dapurnya. Dan pada saat yang bersamaan, penulis-penulis yang baru mulai merintis karier akan layu sebelum berkembang karena prospek menulis yang mulai tidak menjanjikan. Penerbit, untuk bisa tetap bertahan, mungkin akan lebih memberikan prioritas kepada buku-buku pembahasan soal-soal untuk lulus dalam tes-tes tertentu, seperti CPNS, SBMPTN, UN dan lain-lain.
Gebrakan 12 penerbit di Yogyakarta yang tergabung dalam Konsorsium Penerbit Jogja (KPJ) dengan melaporkan kasus pembajakan buku yang kian marak ke ranah hukum harus disikapi oleh pemerintah secara serius. Melawan bisnis buku bajakan jelas jauh lebih bijak ketimbang melakukan razia terhadap buku-buku beraliran kiri yang marak terjadi dalam beberapa bulan belakangan di sejumlah wilayah di Indonesia.
Mengubah Mindset
Ada sebuah adagium yang mengatakan, “Selama buku bagus terbit, selama itu pula para pembajak buku berdiri di belakang kita. Pembajakan buku tidak bisa dihentikan. Yang bisa dihentikan hanyalah kehendak untuk tidak membelinya”.
Mengandalkan pemerintah sendirian dalam memerangi masalah buku ibarat mencari sebuah jarum jahit dalam tumpukan jerami. Melawan industri buku bajakan harus dimulai dari pola pikir masyarakat sendiri. Selama ini kita terlalu permisif dan sering menganggap pembajakan buku merupakan hal yang biasa. Pembiasan yang seolah-olah menjadi legitimasi tidak tertulis ini bahkan sering dijumpai dalam institusi-institusi pendidikan kita, mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi. Aktifitas memfotokopi isi buku sebagian atau seluruhnya sering diterima sebagai tindakan yang wajar. Alasannya adalah karena untuk keperluan proses belajar-mengajar.
Dosen dalam mengampu mata kuliah juga kerap memberikan beberapa buku referensi kepada mahasiswa untuk di-fotocopy secara mandiri guna keperluan belajar, penyelesaian tugas perkuliahan atau sebagai bahan ujian. Malah, yang lebih parah, ada pula oknum-oknum dosen yang justru menggandakan buku-buku original untuk kemudian dijual kepada mahasiswa sebagai diktat atau buku penuntun dalam belajar. Perpustakaan sekolah dan kampus juga demikian. Dengan alasan keterbatasan jumlah, buku-buku tertentu yang laris manis dipinjam oleh pelajar dan mahasiswa diperbanyak (kemungkinan besar tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit) untuk sekedar menambah koleksi perpustakaan.
Pembiasaan-pembiasaan tadi sering disalahartikan sebagai wujud perjuangan demokratisasi terhadap akses menuju ilmu pengetahuan. Sangat ironis sebetulnya ketika institusi pendidikan terlibat dalam pembajakan buku. Padahal selama ini sekolah dan kampus selalu hadir dengan seruan anti plagiarisme kepada pelajar, mahasiswa dan dosen ketika hendak membuat karya tulis ilmiah, melakukan penelitian atau menulis tugas akhir. Seharusnya institusi pendidikan berdiri paling depan melawan pembajakan buku.
Intinya, untuk mengubah tren buruk ini, kita harus mulai berani menggunakan akal sehat dan hati nurani. Sebelum membeli buku bajakan, kita harus bisa berpikir reflektif bahwa dengan membeli buku bajakan berarti kita telah ikut merugikan penulis yang sudah bersusah payah berkarya. Dan sebaliknya, dengan membeli buku-buku asli, kita sudah belajar menghargai buah pemikiran intelektualitas penulis.
==
*Penulis adalah kolumnis lepas, guru SMP/SMA Sutomo 2 Medan dan dosen PTS.
==
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya orisinal, belum pernah dimuat dan tidak akan dimuat di media lain, disertai dengan identitas atau biodata diri singkat (dalam satu-dua kalimat untuk dicantumkan ketika tulisan tersebut dimuat). Panjang tulisan 4.000-5.000 karakter. Kirimkan tulisan dan foto (minimal 700 pixel) Anda ke email: [email protected].