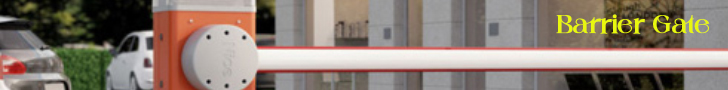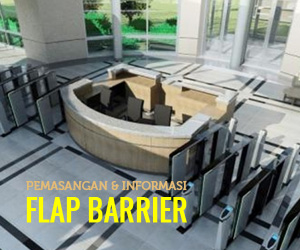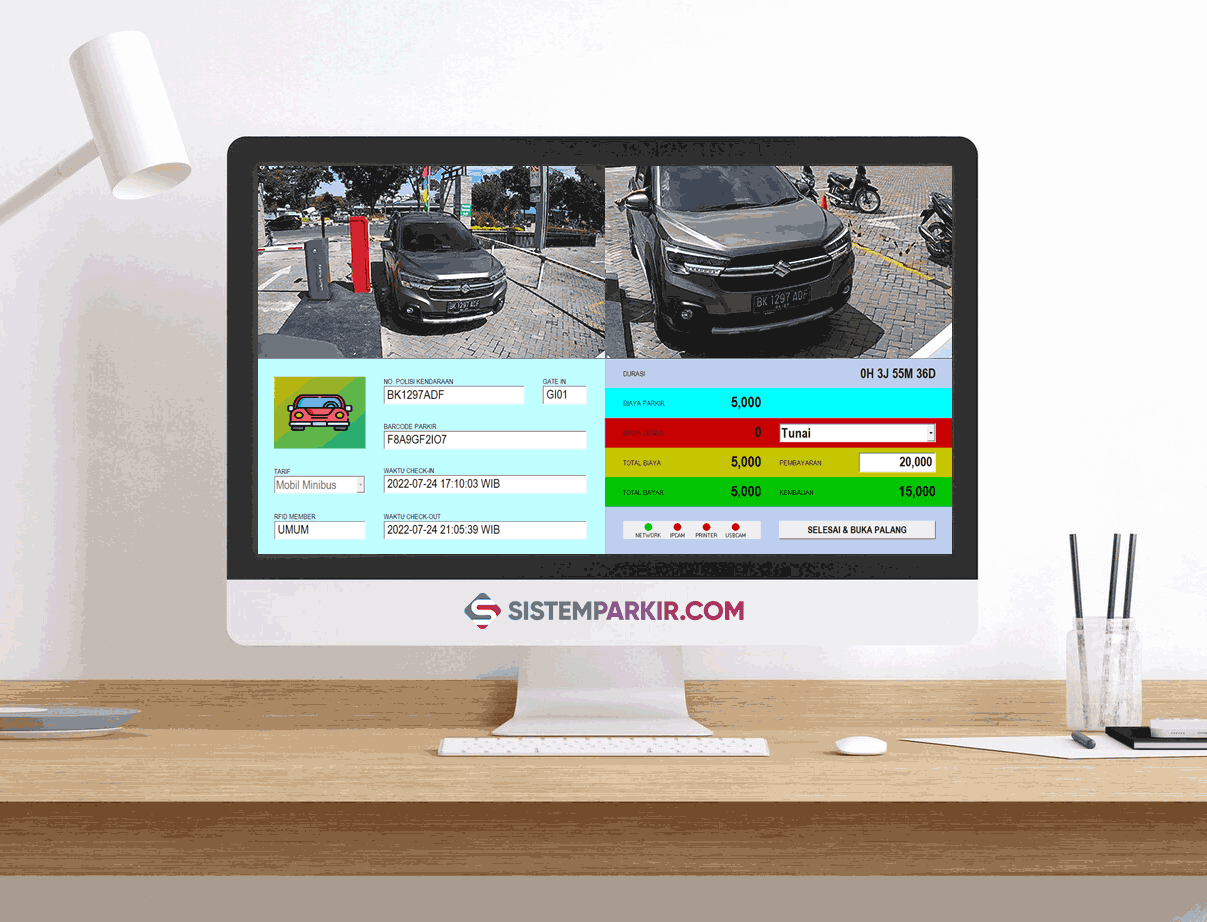PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak 2020 di 270 daerah sudah usai. Secara umum, kendati pelaksanaannya di tengah pandemi, pilkada kali ini patut diapresiasi karena berlangsung dengan suasana yang relatif kondusif. Hanya saja, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Salah satu hal yang paling mendesak untuk dievaluasi adalah menyoal mekanisme penyelesaian hasil pilkada (PHP) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, bahwa peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan memiliki selisih suara sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini:
Jumlah penduduk
Persyaratan selisih suara
< 2.000.0000 ==========2 %
2.000.000-6.000.000 ====1,5%
6.000.000-12.000.000 ===1%
>12.000.000 ==========0,5%
Adapun peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan selisih suara dengan calon pemilik suara terbanyak sebagaimana dijelaskan oleh tabel berikut:
Jumlah penduduk
Persyaratan selisih suara
< 250.0000 ========2 %
250.000-500.000 ===1,5%
500.000-1.000.000 ==1%
>1.000.000 ========0,5%
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang sangat urgen di dalam penentuan pemenang Pilkada, karena putusan MK bersifat final dan mengikat. Sayangnya, banyak perkara perselisihan hasil Pilkada yang bermuara di MK akhirnya kandas hanya karena persyaratan-persyaratan formalitas, tetapi tidak substansial yang diatur dalam UU.
Perkara-perkara yang kandas tersebut dianggap tidak memenuhi syarat memenuhi ambang batas selisih suara antara pemohon/penggugat dengan peraih suara terbanyak di daerah yang bersangkutan. Hanya dengan alasan tersebut, MK pun tidak membahas sama sekali substansi permohonan.
BACA JUGA: Wajah Pilatus dalam Penegakan Hukum Kita
Sebagai contoh, dari 153 perkara PHP yang masuk ke MK pada tahun 2018, hanya 9 (sembilan) perkara PHP yang dianggap memenuhi syarat tersebut untuk ditindaklanjuti dalam persidangan selanjutnya seperti Solok Selatan, Kuantan Singingi, Bangka Barat, Kota Baru, Muna, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Membramo Raya dan Teluk Bintumo. Dasar pertimbangan MK saat itu sangat normatif, yakni sesuai dengan perintah UU. Sederet pertanyaan kemudian menelisisk di benak para pemerhati hukum dan demokrasi. Sesederhana angka itukah makna keadilan menurut MK? Bukankah sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guradiant of constitution) MK harus melindungi hak konstitusional warga negara akan sebuah perhelatan pilkada yang fair dan konstitusional?
Terobosan MK
Akibat keresahan publik tersebut, maka MK melakukan terobosan hukum dalam menangani sengketa hasil Pilkada 2020. Ambang batas PHP yang sebelumnya dijadikan syarat formil, kini diubah menjadi syarat materil (masuk dalam materi pokok perkara). Artinya, setiap perkara PHP yang masuk akan diperiksa oleh MK ,kecuali perkara tersebut kemudian ditarik kembali oleh pemohon. Hasilnya, sebanyak 132 perkara PHP diregistrasi oleh MK dari 136 permohonan yang masuk. Angka ini jauh signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.
Sesuai dengan Hukum Acara PHP di MK, maka 132 perkara tersebut akan masuk ke sidang pemeriksaan, baik untuk pembacaan permohonan, mendengar keterangan termohon (KPU), pihak terkait dan Bawaslu. Syarat ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada tersebut kemudian akan dijadikan acuan dalam pertimbangan putusan akhir. Sebagaimana kita ketahui, Putusan MK dalam Perkara PHP dibagi dalam 3 bagian yakni menolak, mengabulkan sebagian dan mengabulkan seluruhnya.
Terobosan MK menggeser ambang batas sengketa pilkada dari syarat formil menjadi syarat materil tersebut patut diacungi jempol. Alasannya sederhana. Pengaturan ambang batas yang demikian di dalam UU merupakan salah satu bentuk simplifikasi permasalahan pilkada dan mempersempit kesempatan bagi warga negara dalam mencari keadilan. Padahal, pelanggaran-pelanggaran yang lebih masif juga sangat berpotensi terjadi dalam pilkada dengan selisih suara yang jauh lebih besar. Terutama ketika Pilkada tersebut diikuti oleh para petahana dan pemilik kuasa modal. Maka sangat disayangkan ketika pembuat UU tidak mempertimbangkan hal tersebut.
Syarat ambang batas selisih suara juga akan menjadi bom waktu yang dapat mencederai pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam berdemokrasi. Bukan tak mungkin syarat ambang batas ini akan menjadi strategi jitu para peserta pilkada supaya mengusahakan perbedaan suara lebih dari 2 persen. Harapannya tentu supaya perkara tersebut tidak memenuhi syarat formal untuk diajukan ke MK. Logika sederhananya, selisih suara yang signifikan hanya berpotensi terjadi dalam Pilkada yang tidak fair.
Penulis tidak sependapat dengan pendapat yang menyatakan bahwa pmberlakuan ambang batas tersebut dalam jangka panjang merupakan salah satu bentuk rekayasa sosial dalam menciptakan budaya hukum dan politik masyarakat Indonesia (Kompas, 22/1). Hukum sebagai rekayasa sosial (law is a tools of social engineering) yang dimaksud Roscoe Pound tidak sesederhana itu. Bukan sebagai hukum yang membatasi ruang bagi masyarakat dalam mencari keadilan, tetapi hukum yang mampu mengubah perilaku masyarakat kepada hal yang lebih baik. Tidak justru menciptakan peluang baru bagi masyarakat untuk berbuat curang demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Memang, kalau kita kembali ke belakang, pencantuman ambang batas dalam Pasal 158 UU Pilkada tersebut merupakan salah satu ‘upaya’ DPR dan Presiden untuk merayu MK agar bersedia kembali mengadili perkara PHP. Perlu diketahui, sebelumnya MK sudah memutuskan bahwa MK tidak berwenang mengadili sengketa hasil pilkada, namun berhubung karena pengadilan pemilu sebagaimana diamanatkan oleh UU Pilkada belum juga terbentuk, maka penyelesaian perkara PHP ini dikembalikan untuk sementara ke MK. Untuk meminimalisir beban kerja MK, maka dihadirkan ambang batas sengketa pilkada sebagai saringan atau seleksi awal perkara Pilkada.
Diatur dalam Undang-Undang
Penulis yakin, terobosan hukum yang dilakukan MK adalah demi keadilan substansial, bukan semata-mata keadilan prosedural. Sebab MK bukanlah sekadar Mahkamah Kalkulator yang menghitung perselisihan suara yang didapatkan oleh para peserta Pilkada, melainkan harus mencari permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di balik perselisihan suara tersebut. Untuk menguatkan pergeseran ambang batas dari syarat formil menjadi syarat materil, maka ke depan, sudah seharusnya ketentuan tersebut diatur lebih jelas ke dalam UU.
====
Penulis mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UGM Yogyakarta; Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan; Pemilik channel youtube: Januari Sihotang).
====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG), data diri singkat/profesi/kegiatan (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Gunakan kalimat-kalimat yang singkat (3-5 kalimat setiap paragraf). Judul artikel dibuat menjadi subjek email. Tulisan TIDAK DIKIRIM DALAM BENTUK LAMPIRAN EMAIL, namun langsung dimuat di BADAN EMAIL. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]