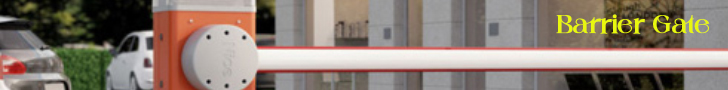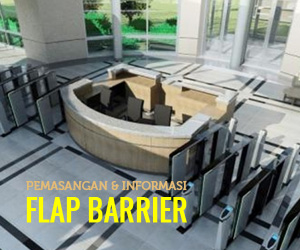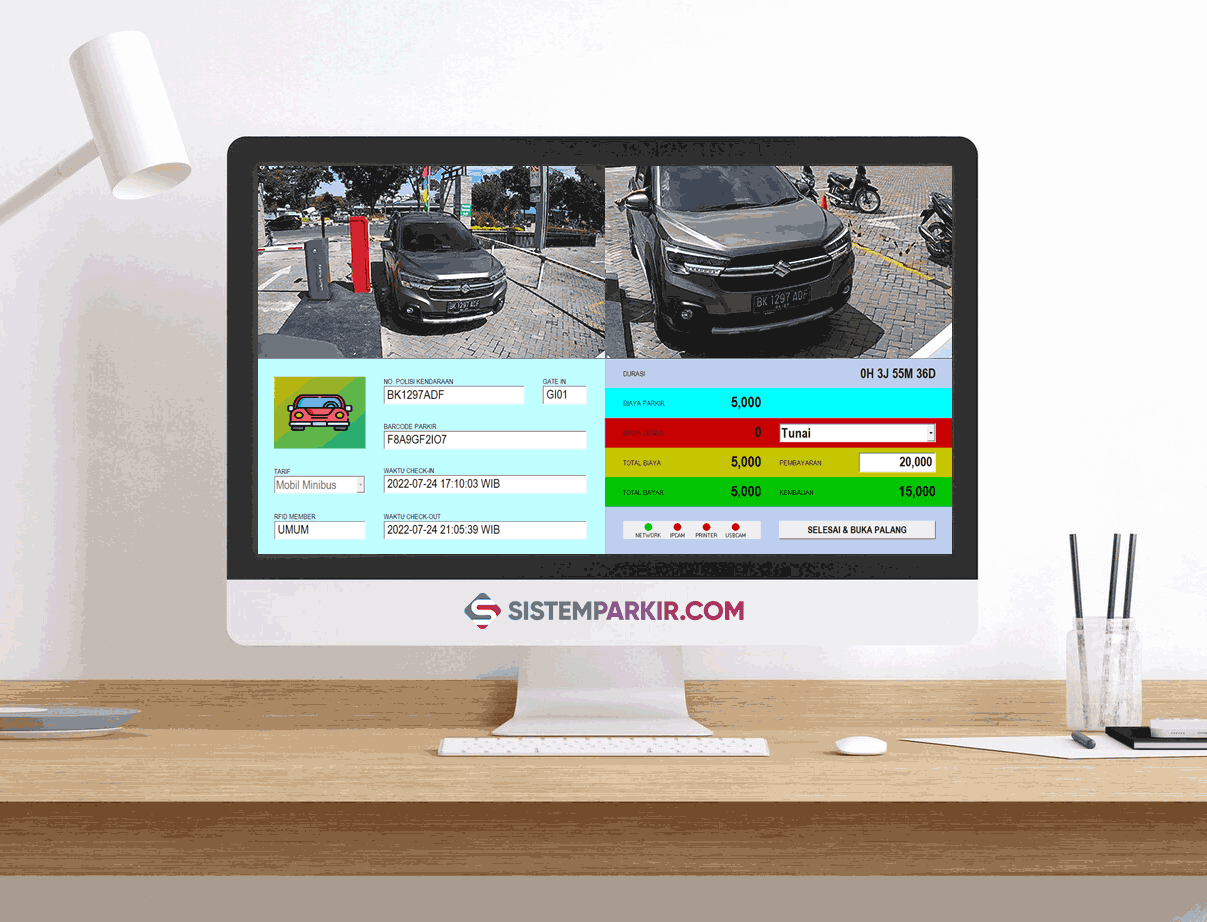BEBERAPA bulan sebelum penyelenggaraan Asesmen Sekolah tingkat SMA tahun 2023, saya merasa kecewa dengan ulah dua murid di kelas saya. Sebut saja Siti dan Fajar (bukan nama sebenarnya). Keduanya tidur saat jam pelajaran berlangsung. Mereka memang akhirnya bangun—karena saya suruh—meski tampak kesulitan menahan kantuk di sisa jam pelajaran.
Kekecewaan yang saya alami bukan tanpa alasan. Mereka kerap ‘ngantuk-ngantuk’ saat mengikuti mata pelajaran Bahasa Inggris yang saya ampu. Mereka selalu pasif dan terlihat tidak punya motivasi sama sekali. Nilai ujian harian keduanya sering tidak tuntas hingga nyaris selalu mengikuti ujian perbaikan nilai (remedial).
Mungkin akan mudah memberi mereka label bodoh, pemalas, tidak peduli masa depan dan sebutan-sebutan tidak mendidik lainnya. Tapi, saya tidak melakukan itu. Saya putuskan untuk memanggil mereka secara terpisah. Kami berbicara baik-baik.
Usut punya usut, Siti dan Fajar telah bekerja. Konsentrasi mereka lebih tercurah untuk pekerjaan, sehingga berdampak pada pembelajaran dalam kelas. Siti sedang dalam jalur yang menjanjikan untuk menjadi seorang selebgram sukses. Meski belum populer dalam skala nasional, followers-nya di Instagram mencapai angka 12 ribu lebih.
Konon, untuk bisa dikatakan sebagai selebgram, seseorang harus punya follower minimal 20.000. Dia sering di-endorse untuk mempromosikan produk-produk makanan, pakaian, resto, ojek online, tempat wisata dan lain-lain. Tiap kali dia memberi testimoni, cara bicaranya lugas, menarik dan tidak kalah jika dibandingkan dengan selebgram-selebgram Indonesia yang sudah punya nama. Siti mengakui kalau dia sering kurang tidur karena sibuk membuat konten.
BACA JUGA: Menyoal Kamtibmas Kota Medan
Fajar lain lagi. Dia bekerja sebagai agen asuransi. Saat saya tanya soal pekerjaannya, dia dengan gamblang menjelaskan secara detail. Ujung-ujungnya dia malah mempromosikan produk-produk asuransi plus investasi untuk saya. Semua dia lakukan bak agen asuransi yang sudah berpengalaman selama bertahun-tahun.
Padahal dia mengaku baru menggeluti profesi itu sekitar tiga bulan terakhir setelah mengikuti sejumlah training dan lulus ujian AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Nasabah Fajar juga sudah cukup banyak sehingga komisi yang dia dapat sebagai agen juga lumayan besar.
Sama dengan Siti, Fajar sering tidur di atas jam 12 malam karena mem-follow up calon nasabah atau membuat ilustrasi kontrak asuransi. Di akhir pembicaraan, dia memberikan kartu tanda agen miliknya kepada saya. “Siapa tahu, Sir mau gabung, kontak saya, ya?” ucapnya dengan antusias.
Apa yang dilakukan Siti dan Fajar tadi sangat berbanding terbalik dengan di kelas. Saat saya memberikan tugas presentasi yang menuntut kemampuan berbicara, misalnya, seingat saya, tak pernah sekalipun mereka selugas dan sehebat itu.
Mereka lebih banyak diam. Tugas juga sering tidak selesai. Tapi untuk urusan pekerjaan yang terkadang dikejar deadline, mereka sanggup tidur hanya dua sampai tiga jam dalam satu malam, padahal besoknya harus sekolah.
Tak cuma pada pelajaran saya, beberapa rekan guru lain yang juga mengajar di kelas mereka ternyata menghadapi persoalan serupa.
Perbedaan totalitas Siti dan Fajar saat bekerja dengan ketika belajar di kelas betul-betul timpang. Di ranah akademis, boleh dikatakan pencapaian mereka kurang atau buruk. Tapi, jangan cepat-cepat memberi vonis bahwa keduanya adalah anak-anak tidak cerdas dan nir prestasi.
Selama ini pendidikan kita sering terjebak. Kecerdasan dan prestasi selalu dikaitkan dengan keberhasilan akademik. Kamu adalah anak yang cerdas dan berprestasi kalau nilai raportmu bagus-bagus, kalau kamu juara kelas, kalau kamu menyabet medali dalam OSN (Olimpiade Sains Nasional)! Stigma ini yang terus-menerus terpelihara secara kolektif sehingga menancap begitu tajam dalam pola pikir kita.
Guru-guru, sadar atau tidak sadar, dengan ‘egoisme’ dan ‘fanatisme’ keilmuan masing-masing, tak jarang menjadikan keberhasilan dalam kelas sebagai indikator kesuksesan di masa depan.
Orang tua dan masyarakat juga demikian. Saya berani bertaruh. Pasti lebih banyak orang tua yang lebih rela menggelontorkan uang belasan juta rupiah atau lebih untuk anaknya ikut bimbel agar lulus PTN (Perguruan Tinggi Negeri) favorit, ketimbang les vokal kendati si anak punya bakat menyanyi.
Kita akan cenderung lebih terpukau melihat anak yang juara OSN Matematika ketimbang anak yang memiliki kemampuan hebat dalam stand up commedy—untuk sekadar menyebut contoh.
Padahal, seperti yang pernah dicetuskan Howard Gardner, setidaknya ada sembilan tipe kecerdasan manusia: kecerdasan visual-spasial, kecerdasan linguistik-verbal, kecerdasan logis-matematika, kecerdasan kinestetik-jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalistik dan kecerdasan eksistensial. Semua kecerdasan ini penting dan diperlukan dalam hidup setiap individu.
Siti dan Fajar boleh jadi ‘tidak cerdas’ di dalam kelas. Tapi di luar kelas, mereka anak cerdas. Mereka bahkan patut diacungi jempol karena sudah mampu mencari uang sendiri dan meringankan beban orang tua. Ini bukan hanya soal materi, tetapi bukankah literasi keuangan itu penting? Lagipula, mereka juga telah turut membantu pemerintah karena tidak menambah deretan angka pengangguran—PR berat bangsa kita dari tahun ke tahun.
Oh iya, mereka juga ternyata akan melanjutkan pendidikan ke PTS (Perguruan Tinggi Swasta) yang menyediakan kelas malam. Saat saya tanya kenapa tidak mencoba PTN, jawaban mereka sama: ingin punya waktu untuk bekerja pagi hingga sore hari. Luar biasa!
Kasus Siti dan Fajar menjadi contoh yang sangat baik untuk menata ulang kerangka berpikir kita soal pendidikan di negeri ini. Dari mereka saya semakin memahami makna merdeka belajar. Belajar tidak boleh kaku (rigid). Pembelajaran tidak hanya sebatas implementasi rambu-rambu yang telah digariskan dalam RPP dan Silabus. Dalam konteks yang lebih luas, pembelajaran harus mengakomodir minat dan kemampuan anak-anak yang berbeda.
Itulah yang saya terapkan pada adik-adik kelas Siti dan Fajar baru-baru ini. Dalam satu pembelajaran mengenai teks naratif (narrative texts), saya memberikan tugas berbentuk project secara berkelompok. Singkatnya, saya meminta beberapa teks naratif berupa dongeng, mitos dan cerita rakyat yang tersedia di dalam buku pelajaran, dipilih salah satu dan kemudian diubah menjadi comic strip sebelum dipresentasikan di depan kelas dalam bentuk story retelling.
Mereka berkolaborasi. Mereka merdeka mengerjakan tugas sesuai keahlian masing-masing. Makanya, saya apresiasi semua anak-anak dalam setiap kelompok dengan nilai yang bagus. Misalnya, dalam satu kelompok, saya mendapati ada anak yang kurang baik dalam sesi menjelaskan saat presentasi. Tapi, dialah orang yang menggambar tokoh-tokoh dalam komik.
Gambarnya sangat bagus. Saya katakan padanya, “Kamu punya bakat menjadi seorang illustrator profesional!” Ada juga anak yang memberi plot twist sehingga cerita dalam versi comic strip mereka jauh berbeda dari cerita aslinya. Saya bilang padanya, “Kamu bisa menjadi penulis novel sehebat JK Rowling!” Ada semangat yang bertambah dan ada rasa percaya diri yang kian tumbuh di wajah anak-anak itu.
Meski saya temukan inspirasi dari Siti dan Fajar, saya tidak serta merta memaklumi kebiasaan buruk soal tidur atau mengantuk dalam kelas. Saya jadi teringat dengan buku professor Rhenald Kasali, Strawberry Generation. Anak-anak seperti Siti dan Fajar adalah generasi strawberry: kreatif dan punya banyak ide, namun rapuh karena mudah menyerah dan sakit hati. Sebagai guru, tugas saya dan tugas guru-guru lainnya adalah mengarahkan dan menggerakkan. Bukan dengan paksaan. Tapi membangkitkan kerelaan.
Dan memang setelah keduanya saya ajak berkomunikasi, sikap ogah-ogahan belajar mereka tidak lagi saya temukan. Mereka juga tak lagi ngantuk di dalam kelas karena semakin bijak mengatur waktu antara belajar dan bekerja. Setiap kali berpapasan di luar jam belajar dengan saya atau guru-guru lain, baik Siti dan Fajar selalu menyapa dengan penuh rasa hormat. Dengan kata lain, mereka menjunjung tinggi budaya ketimuran kita.
Ini sesuai dengan slogan di sekolah kami: Karakter OK, Prestasi Yes, dan sejalan dengan konsep Merdeka Berbudaya ala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak cukup hanya prestasi, anak-anak Indonesia juga harus punya karakter yang mumpuni demi menyongsong Generasi Emas 2045.
====
Penulis guru SMP/SMA Sutomo 2 Medan.
====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), data diri singkat (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]